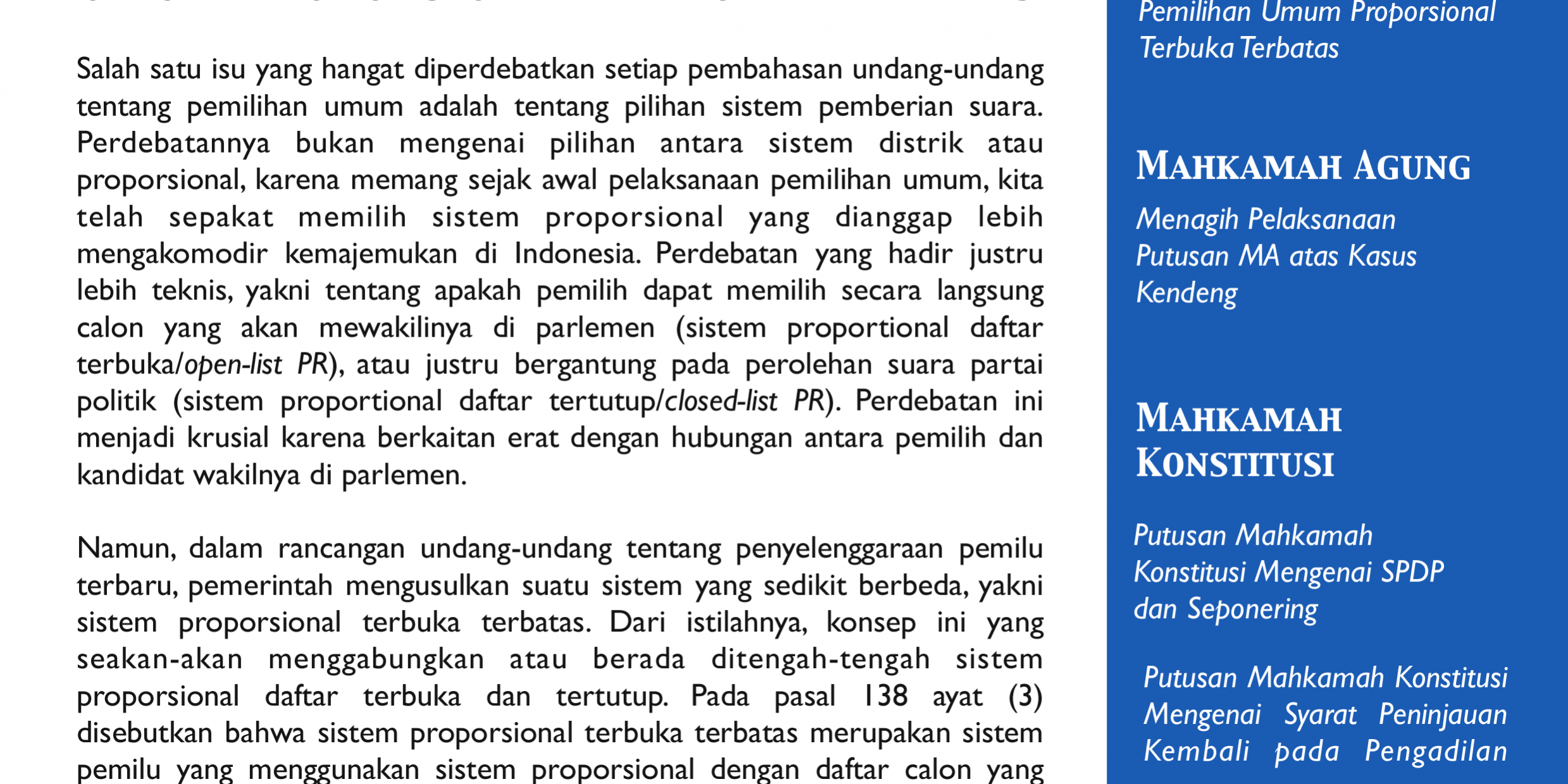Pemilu
KONSTITUSIONALITAS SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA TERBATAS
Salah satu isu yang hangat diperdebatkan setiap pembahasan undang-undang tentang pemilihan umum adalah tentang pilihan sistem pemberian suara. Perdebatannya bukan mengenai pilihan antara sistem distrik atau proporsional, karena memang sejak awal pelaksanaan pemilihan umum, kita telah sepakat memilih sistem proporsional yang dianggap lebih mengakomodir kemajemukan di Indonesia. Perdebatan yang hadir justru lebih teknis, yakni tentang apakah pemilih dapat memilih secara langsung calon yang akan mewakilinya di parlemen (sistem proportional daftar terbuka/open-list PR), atau justru bergantung pada perolehan suara partai politik (sistem proportional daftar tertutup/closed-list PR). Perdebatan ini menjadi krusial karena berkaitan erat dengan hubungan antara pemilih dan kandidat wakilnya di parlemen.
Namun, dalam rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu terbaru, pemerintah mengusulkan suatu sistem yang sedikit berbeda, yakni sistem proporsional terbuka terbatas. Dari istilahnya, konsep ini yang seakan-akan menggabungkan atau berada ditengah-tengah sistem proporsional daftar terbuka dan tertutup. Pada pasal 138 ayat (3) disebutkan bahwa sistem proporsional terbuka terbatas merupakan sistem pemilu yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut yang terikat berdasarkan penetapan partai politik. Selanjutnya dijelaskan bahwa penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dari partai politik peserta pemilu didasarkan pada perolehan kursi partai politik di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan nomor urut calon sesuai urutan yang tercantum pada surat suara.
Jika dibaca lebih lanjut, apa yang diusulkan oleh pemerintah tersebut sebenarnya bukan merupakan varian dari system proporsional daftar terbuka, melainkan merupakan konsep sistem proporsional daftar tertutup (closed list PR) yang sebenarnya. Mengapa demikian? Secara historis, konsep proporsional tertutup (closed list PR) yang selama ini diterapkan di Indonesia telah mengalami pergeseran dari konsep asli yang dikenal di dunia (Pipit R. Kartawidjaja, 2002).
Di Indonesia, sistem proporsional daftar tertutup (closed list PR) biasa diartikan sekedar memilih lambang atau gambar partai, tanpa mengetahui daftar nama calon anggota legislative. Sedangkan pada konsep aslinya, sebagaimana diterapkan di Jerman, sistem proporsional daftar tertutup (closed-list PR) adalah sistem dengan daftar baku. Artinya, daftar nama urutan calon anggota legislatif sudah ditetapkan lebih dulu oleh partai peserta pemil, yang biasanya dipilih secara demokratis dalam kongres partai. Dengan demikian, apa yang diusulkan pemerintah bukan merupakan varian dari sistem proportional daftar terbuka (open list PR) atau jalan tengah dari sistem proporsional daftar terbuka dan tertutup, melainkan merupakan konsep dasar dari proporsional daftar tertutup itu sendiri (closed-list PR).
“Selain itu, usulan yang diajukan tersebut perlu untuk kembali dievaluasi mengenai konstitusionalitasnya mengingat Mahkamah Konstitusi pernah memutus mengenai hal serupa pada putusan nomor 22-24/PUU-VI/2008. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa makna kedaulatan rakyat yang terkandung pada pasal Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 seharusnya dimaknai sebagai ruang bagi rakyat untuk memilih secara langsung siapa yang dikehendakinya dalam pemilihan umum, termasuk dalam pemilihan umum legislatif. Mahkamah Konstitusi memandang bahwa sistem ini dapat meningkatkan partisipasi pemilih, mempermudah perhitungan suara, serta dapat meminimalisir konflik dan mengikis oligarki di internal partai politik. Selain itu, dari perspektif hak asasi manusia, mekanisme proporsional dengan daftar terbuka (open-list PR) dapat memberikan kedudukan dan kesempatan yang sama bagi setiap calon anggota legislatif untuk bersaing dalam pemilihan umum. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem proporsional terbuka-terbatas yang diusulkan oleh pemerintah dalam rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu bertentangan dengan konstitusi. (MS)
Mahkamah Agung
Menagih Pelaksanaan Putusan MA atas Kasus Kendeng
Pada Oktober 2016, Mahkamah Agung melalui Putusan No. 99 PK/TUN/2016 membatalkan SK Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 Tahun 2012 tentang izin lingkungan kegiatan penambangan dan mewajibkan Gubernur untuk mencabut SK tersebut. Namun, sebelum mendapatkan salinan putusan, Gubernur mengeluarkan SK Gubernur No. 660.1/30 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang izin lingkungan kegiatan penambangan bahan baku semen dan pembangunan serta pengoperasian pabrik semen di Rembang. Gubernur telah mengabaikan proses hukum dan didesak untuk menghormati dan melaksanakan putusan MA. Atas desakan itu, Gubernur mengeluarkan SK baru.
Terdapat dua hal dalam SK Gubernur tersebut. Pertama, menyatakan batal dan tidak berlaku SK Gubernur No. 660.1/30 tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang izin lingkungan kegiatan penambangan bahan baku semen dan pembangunan serta pengoperasian pabrik semen di Rembang. Kedua, memerintahkan PT Semen Indonesia untuk menyempurnakan dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan/ Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL/ RPL) sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Artinya, Gubernur masih memberikan kesempatan pada PT Semen Indonesia untuk melakukan kegiatan penambangan dan pengoperasian semen dengan syarat penyempurnaan dokumen-dokumen terkait. Hal ini jelas melanggar putusan MA.
Pasal 40 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyatakan bahwa dalam hal izin lingkungan dicabut maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. Dalam konteks Kendeng, maka izin kegiatan penambangan bahan baku semen dan pengoperasian pabrik artinya juga dibatalkan. Patut diingat, perkara Kendeng juga bukan semata-mata masalah ketidaklengkapan dokumen. Namun lebih dari itu, masalah dampak lingkungan akibat kegiatan penambangan semen. Pertimbangan hakim dalam putusan MA menjadi menarik untuk dicermati. Walaupun ahli dari pemerintah yang hadir berpendapat bahwa tidak ada larangan untuk melakukan penambangan di atas kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) sehingga dapat diberikan izin khusus, Hakim berpendapat lain. Hakim menilai perlunya penerapan asas kehati-hatian dan asas kecermatan dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) oleh penyelenggara negera agar lebih mengutamakan “menghindari potensi kerusakan/bahaya daripada mengambil manfaat.” Dengan kata lain, untuk mendapatkan manfaat, wajib menjauhi potensi kerusakan.
Pasal 23 ayat (1) UU PPLH mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak besar dan penting wajib didukung dengan dokumen AMDAL. Dalam putusan MA, Hakim mempertimbangkan bahwa penyusunan AMDAL pada kawasan itu harus dilakukan secara khusus dengan memperhatikan asas kelestarian, asas kecermatan, dan kehati-hatian. Sementara itu, wilayah pertambangan semen Kendeng berada di kawasan Cekungan Air Watu Putih yang dilindungi oleh Keputusan Presiden No. 26 Tahun 2011 tentang Cekungan Air Tanah. Karena itu, kawasan sekitarnya merupakan bagian dari kawasan lindung yang fungsi utamanya melindungi kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, warga di kawasan sekitar menggantungkan hidupnya pada kawasan CAT tersebut. Jika penambangan semen tetap dilakukan di kawasan CAT tersebut, kebutuhan warga atas air terganggu.
Padahal, hak atas air merupakan bagian dari hak asasi manusia, walaupun tidak disebutkan secara khusus. Pasal 28A UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Lebih lanjut, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sidang Umum PBB pada 28 Juli 2010 menghasilkan Resolusi No. 64/292 yang mengakui bahwa hak atas air merupakan hak asasi manusia. Komentar Umum Nomor 15 menegaskan bahwa hak asasi manusia memberikan hak kepada setiap orang atas air yang memadai, aman, bisa diterima, bisa diakses secara fisik, dan mudah didapatkan untuk penggunaan personal dan domestik. Dalam konteks Kendeng yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidupnya pada pertanian, keberadaan air menjadi vital. Kesulitan akses atas air hanya akan menimbulkan pelanggaran hak-hak lain yang muncul, seperti hilangnya hak atas pekerjaan, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Karena itu, publik patut menagih Gubernur untuk melaksanakan putusan MA. Upaya melalui proses hukum di pengadilan hanyalah satu dari sekian tindakan yang dilakukan warga Kendeng untuk menolak tambang semen. Terdapat upaya lain seperti dialog, aksi bertahan di tenda, membangun jejaring, dan pendekatan budaya yang tidak mudah. Sejumlah warga juga mengalami luka-luka dalam aksi bertahan di tenda depan wilayah pembangunan tambang semen. Konflik horizontal terjadi pada sesama warga, antara yang mendukung dan yang menolak pembangunan tambang semen. Selain itu, juga dilakukan pengkriminalan terhadap warga yang menolak tambang semen di Kendeng. Keadaan seperti ini harus berhenti. Tidak boleh ada lagi celah untuk mengakali putusan MA dengan memberi kesempatan perbaikan dokumen AMDAL, RKL, dan RPL.
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI SPDP DAN SEPONERING
Reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia kembali mendapatkan stimulus melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan yang dimaksud adalah Putusan MK No.130/PUU-XIII/2015 yang menguji UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 yang menguji UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). Meskipun putusan-putusan tersebut tidak mengabulkan seluruh permohonan atau bahkan tidak sesuai dengan rumusan pasal yang dimohonkan, namun tetap mendapat apresiasi oleh para pemohon dan aparatur penegak hukum lainya.
Pengaju Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah Choky Risda Ramadhan, Carolus Boromeus, Usman Hamid, dan Andro Supriyanto. Pasal-pasal yang diujikan antara lain pasal 14 b dan i; pasal 109 ayat (1); pasal 138 ayat (1) dan (2); serta pasal 139. Namun, MK hanya mengabulkan Pasal 109 ayat (1). Menurut MK, pasal 109 (1) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.” Menurut MK, tertundanya penyampaian SPDP dapat menyebabkan terlanggarnya asas due process of law sebagaimana dijamin pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Ada hal menarik dari pasal 109 (1) yang dikabulkan MK. Sebenarnya pemohon memiliki usulan rumusan baru yang berbeda seperti: pihak yang wajib diberikan “kepada penuntut umum”, kemudian soal jangka waktu yaitu “satu hari setelah dikeluarkan SPDP” dan akibat hukum jika tidak memberitahukan hal tersebut adalah “batal demi hukum”. Namun, MK memiliki pertimbangan tersendiri untuk memperluas pihak yang wajib diberitahukan juga kepada korban/pelapor dan terlapor untuk menghindari kerugian konstitusional serta memberikan waktu mempersiapkan bahan. Mengenai batas waktu, MA menganggap cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan SPDP dalam 7 hari. Akan tetapi, dalam pertimbangan MK tidak menjelaskan alasan menolak permohonan adanya akibat hukum jika tidak terlaksananya pemberitahuan SPDP, sehingga kurang memberikan tekanan bagi penyidik untuk melaksanakan norma tersebut.
Sedangkan Irwansyah dan Dedi memohonkan pengujian terhadap Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan beserta penjelasannya. MK dalam Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 kemudian memutuskan bahwa penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.” Soal seponeering, MK merasionalisasikan bahwa seponering tidak melanggar prinsip equality before the law sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga tetap dibutuhkan demi melindungi masyarakat luas.
Pasal-pasal dari UU Kejaksaan yang dimohonkan pengujiannya antara lain adalah untuk membatalkan Pasal 35 huruf c; menyatakan Penjelasan Pasal 35 huruf c menjadi, “setelah memperoleh persetujuan tertulis dari DPR”; atau menyatakan penjelasan pasal 35 huruf c menjadi, “wajib memperhatikan dan mengikuti saran dan pendapat mayoritas dari DPR, MA, dan Kepolisian”. Akan tetapi, MK menafsirkan berbeda dengan rumusan yang dimohonkan pemohon yaitu hanya menambahkan kata “wajib” dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c. Meskipun MK berpandangan tafsiran tersebut telah memberikan ukuran yang jelas, tapi MK seharusnya juga menafsirkan makna dari “badan-badan kekuasaan negara” agar tidak menimbulkan multi tafsir dalam pelaksanaan.
Berdasarkan dua putusan diatas, MK kembali membentuk norma baru dengan model putusan inkonstitusional bersyarat. Dalam pertimbangan putusan MK telah menunjukan tidak hanya terfokus pada usulan rumusan norma baru yang diajukan pemohon, namun juga mencari rumusan norma yang lebih komprehensif. Misalkan pada Putusan MK No.130/PUU-XIII/2015 tentang SPDP, MK memperluas subjek yang diberikan kepada pelapor dan terlapor/korban demi melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Akan tetapi dalam Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang seponeering, MK belum memperhatikan hal yang sifatnya implementasi seperti kejelasan lembaga yang memberikan saran dan pendapat.
Legislasi
Pemerintah Menerbitkan Regulasi Holding BUMN
Baru-baru ini Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72/2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Hadirnya peraturan ini membuat pemerintah leluasa dalam membentuk perusahaan holding BUMN pada masing-masing sektor.
Meski demikian, kontroversi tetap mengiringi setelah PP No. 72/2016 terbit. Masalah utama yang mencuat dalam sejumlah media adalah terkait dengan pengalihan saham-saham BUMN tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN). Maknanya, pengalihan saham-saham BUMN ini dilakukan tanpa harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tidak kurang, pengamat kebijakan, anggota DPR, dan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan komentar soal penentangan atas PP ini.
Apakah memang benar demikian isi dari PP tersebut? Jika kita membaca PP tersebut secara jelas, maka kita perlu membaca secara utuh terhadap PP 44/2005 yang menjadi peraturan asal terhadap PP 72/2016 yang mengubahnya. Secara umum, PP 44/2005 mengatur mengenai tata cara penyertaan, penambahan penyertaan, dan termasuk pengurangan penyertaan negara dalam bentuk saham kepada BUMN atau perseroan terbatas lain yang sebelumnya belum ada saham negara disitu. Bahkan, pengurangan penyertaan negara salah satunya adalah melalui privatisasi atau penjualan saham BUMN kepada pihak lain (Pasal 9) dan mekanisme ini tidak tidak diatur dalam PP 44/2005 sebagaimana diubah dengan PP 72/2016. Pengaturan soal privatisasi sudah diatur dalam PP No. 33/2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana diubah dengan PP No. 59/2009. Dalam Pasal 3 itulah diatur mengenai persetujuan DPR terhadap privatisasi melalui kesepakatan RAPBN.
Secara khusus, substansi PP 72/2016 adalah mengenai mekanisme penyertaan modal saham BUMN kepada BUMN lain dalam rangka pembuatan skema induk perusahaan BUMN (holding) dan anak perusahaan BUMN. Substansi penting dari PP 72/2016 adalah diaturnya saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas sebagai salah satu kekayaan negara namun tentu saja kekayaan negara yang dipisahkan (Pasal 2 ayat (2) huruf d). Pengaturan ini menjadi benchmark terhadap penambahan pasal berikutnya (Pasal 2A). Pasal 2A kemudian mengatur mengenai peralihan saham BUMN ke BUMN lain atau PT dimana peralihan tersebut tidak melalui mekanisme APBN.
Terbitnya PP ini secara tidak langsung memberikan ruang tafsir baru yang lebih luas terkait dengan definisi BUMN yang menentukan bahwa BUMN dimiliki langsung oleh negara melalui kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan adanya PP ini dan penambahan satu elemen terkait sumber kekayaan negara untuk kepemilikan BUMN dan PT, maka PP ini juga sekaligus memberikan ruang gerak kepada pemerintah untuk mewujudkan cita-cita pembentukan holding BUMN yang sudah digadang-gadang lebih dari satu dekade lalu. Pembuatan PP bisa dikatakan dianggap lebih realistis ketimbang membuat perubahan atas UU No. 19/2003 tentang BUMN. (MFA)
Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Syarat Peninjauan Kembali pada Pengadilan Pajak dan Hak Pekerja dalam Memperoleh Informasi
Pada Rabu, 11 Januari 2017, Mahkamah Konstitusi telah memutus dua perkara pengujian undang-undang. Perkara pertama yang berkaitan dengan peninjauan kembali ke pengadilan pajak dalam Putusan Nomor 133/PUU-XIII/2015 dinyatakan ‘ditolak untuk seluruhnya’ oleh Mahkamah Konstitusi. Perkara kedua berkaitan dengan hak memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam Putusan Nomor 3/PUU-XIV/2016 dinyatakan ‘pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)’ oleh Mahkamah Konstitusi. Pada dasarnya, terdapat kesamaan dasar pertimbangan dalam memutus kedua perkara itu, yaitu perkara yang diuji bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan implementasi norma.