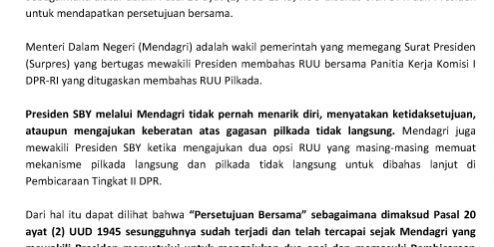Jakarta, 30 September 2014
Pernyataan kaget dan kecewa dari Presiden SBY atas hasil pengambilan keputusan RUU Pilkada dalam Rapat Paripurna DPR 25 September 2014 yang lalu jelas tidak dapat diterima jika dilihat dari aspek tata cara dan prosedur pembahasan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) adalah wakil pemerintah yang memegang Surat Presiden (Surpres) yang bertugas mewakili Presiden membahas RUU bersama Panitia Kerja Komisi I DPR-RI yang ditugaskan membahas RUU Pilkada.
Presiden SBY melalui Mendagri tidak pernah menarik diri, menyatakan ketidaksetujuan, ataupun mengajukan keberatan atas gagasan pilkada tidak langsung. Mendagri juga mewakili Presiden SBY ketika mengajukan dua opsi RUU yang masing-masing memuat mekanisme pilkada langsung dan pilkada tidak langsung untuk dibahas lanjut di Pembicaraan Tingkat II DPR.
Dari hal itu dapat dilihat bahwa “Persetujuan Bersama” sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 sesungguhnya sudah terjadi dan telah tercapai sejak Mendagri yang mewakili Presiden menyetujui untuk mengajukan dua opsi dan memasuki Pembicaraan Tingkat II di DPR.
Apabila benar ada kesungguhan penolakan dari Presiden SBY, hal ini seharusnya disampaikan oleh Presiden SBY melalui Mendagri sebelum memasuki Pembicaraan Tingkat II di DPR. Presiden melalui Mendagri bisa menyatakan ketidaksetujuannya, menarik diri, dan menolak untuk melanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II.
Dalam menolak pengaturan pilkada tidak langsung, Presiden seharusnya menggunakan mekanisme dan tata cara formal yang ada, bukan dengan cara beropini di media sosial sementara wakil resminya mendukung dua opsi yang ada di DPR.
Langkah menyatakan ketidaksetujuan dan menarik diri sebelum masuk ke Pembicaraan Tingkat II pernah dilakukan oleh Presiden SBY baru-baru ini pada pembahasan RUU Tabungan Perumahan Rakyat pada 23 September 2014 lalu. Langkah itu akhirnya menghentikan kelanjutan pembahasan RUU tersebut.
Selain itu, keinginan Presiden SBY untuk tidak mengesahkan atau tidak menandatangani UU Pilkada merupakan tindakan yang sama sekali tidak memiliki dampak hukum terhadap keabsahan undang-undang itu. Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa sebuah RUU yang telah disetujui bersama tetapi tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu 30 hari sejak persetujuan bersama itu akan tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
Tindakan konsultasi Presiden SBY kepada Ketua Mahkamah Konstitusi juga telah mencederai prinsip independensi hakim yang diatur dalam Bangalore Principles of Judicial Conduct, acuan kode etik bagi hakim di seluruh dunia, termasuk hakim konstitusi. Permintaan konsultasi oleh Presiden SBY itu dapat dinilai telah mengganggu independensi MK sebagai lembaga peradilan. Sebagai pemegang kekuasaan yudikatif, MK harus menjaga kemandiriannya serta harus bebas dari pengaruh cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.
Selain itu, konsultasi antara Presiden dan MK juga memiliki potensi konflik kepentingan mengingat Presiden dapat menjadi pihak dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara dan pemakzulan di MK. Terlebih lagi, dalam konteks UU Pilkada, undang-undang ini jelas dapat menjadi objek permohonan pengujian di MK.
Dalam struktur ketatanegaraan, MK juga tidak memiliki peran sebagai penasihat Presiden untuk masalah apapun. Dalam hal kebutuhan pertimbangan atas suatu permasalahan dalam bidang hukum, Presiden memiliki ruang untuk meminta pertimbangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selain itu, Presiden juga dimungkinkan untuk mengonsultasikan permasalahan hukum dengan jajaran di bawahnya, yakni Dewan Pertimbangan Presiden ataupun Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Menyikapi hal-hal tersebut, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyatakan bahwa:
Pertama, Presiden SBY melalui Mendagri telah memberikan persetujuannya kepada dua opsi yang ada dan oleh karenanya “Persetujuan Bersama” sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 sudah terjadi dan telah tercapai. Tidak wajar apabila saat ini Presiden SBY seolah mencari berbagai jalan untuk menolak RUU yang opsi-opsinya diusung oleh Menteri yang mewakilinya sendiri. Wacana yang mendorong agar Presiden SBY menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) tidaklah tepat mengingat tidak terpenuhinya situasi “kegentingan yang memaksa” sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Tidak juga wajar bagi Presiden SBY untuk menyatakan bahwa telah terjadi kegentingan memaksa bagi kondisi yang diusulkan dan disetujui oleh Presiden sendiri. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Presiden SBY terkait UU Pilkada hanya usaha untuk menyelamatkan citra dirinya di akhir masa jabatan, dan karenanya harus ditolak.
Kedua, saat ini terbuka peluang bagi masyarakat luas untuk mengajukan permohonan pengujian (judicial review) UU Pilkada kepada MK. Kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat luas yang merasa hak konstitusionalnya dalam memilih kepala daerah telah dirugikan akibat disahkannya UU Pilkada.
Ketiga, pemerintah baru di bawah kepemimpinan presiden terpilih Joko Widodo harus segera mengusulkan RUU Perubahan atas UU Pilkada yang memuat mekanisme pilkada langsung serta mendesak DPR agar menempatkan RUU Perubahan itu dalam Prioritas Legislasi Tahun 2015.
Kontak: Rizky Argama, Peneliti PSHK, 0812-1983-193