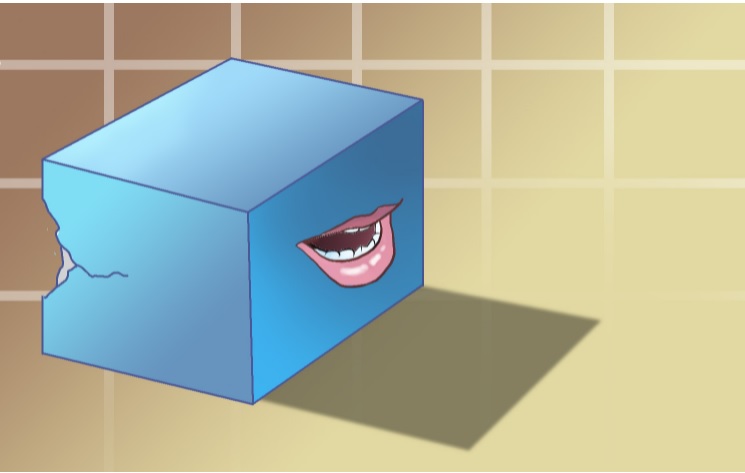
Menteri Sosial menuai kritik ketika memaksa seorang anak penyandang disabilitas rungu untuk berbicara. Ironisnya, hal ini ia pertontonkan dalam acara peringatan Hari Disabilitas Internasional.
Pada mulanya, sang anak menghadiahi sang menteri sebuah lukisan pohon sebagai kritik terhadap kerusakan lingkungan di Indonesia. Dengan dalih berlatih agar lancar berbicara, Risma meminta sang anak menjelaskan secara lisan mengapa ia mengkritik pemerintah untuk selalu menjaga lingkungan. Anak yang malang itu kemudian terlihat kesulitan mengikuti perintah Risma.
Peristiwa tersebut adalah contoh diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Apa pun alasan dan pembelaan Risma, tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan. Risma perlu meminta maaf atas perilakunya yang melanggar hak penyandang disabilitas.
Kasus Risma menunjukkan bahwa ableisme masih menjangkiti pejabat publik. Istilah “ableisme” berasal dari bahasa Inggris able (mampu) sebagai pembeda dari disable (tidak mampu). Ableisme adalah kecenderungan memandang disabilitas sebagai sebuah ketidaksempurnaan, termasuk mengasosiasikannya dengan penyakit.
Dalam banyak kasus, penganut ableisme meyakini bahwa disabilitas bisa disembuhkan sepanjang orang tersebut berusaha melatih dirinya. Pandangan ini persis seperti apa yang dikatakan Risma. Alasan Risma, yang membandingkan sang anak dengan Angkie Yudistia, staf khusus Presiden Joko Widodo yang juga tuli, justru semakin menguatkan bias ableisme.
Menurut Campbell (2009), ableisme menjadi penyebab laten maraknya diskriminasi dan stigmatisasi terhadap penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Perilaku itu bisa lahir secara sengaja ataupun tidak sengaja. Ableisme bisa berbentuk diskriminasi dalam pekerjaan, komentar kasar atau merendahkan, paksaan atau pembungkaman, hingga penyingkiran.
Bentuk diskriminasi yang paling lazim terjadi adalah mengasosiasikan disabilitas sebagai kecacatan. Setelah lahirnya Undang-Undang Penyandang Disabilitas, istilah “penyandang cacat” ditinggalkan karena dinilai merendahkan dan tidak sensitif terhadap keragaman kondisi manusia.
Berbeda dengan pandangan ableisme, disabilitas tak lagi dipandang sebagai penyakit. Tugas negara bukanlah menyembuhkan, melainkan memberi akses yang ramah dan inklusif terhadap penyandang disabilitas. Dalam Undang-Undang Hak-hak Asasi Manusia, penyandang disabilitas berhak menikmati pelindungan dan perlakuan khusus dari negara, yang mewujud dalam kewajiban negara untuk memberi akomodasi dan aksesibilitas agar penyandang disabilitas bisa berpartisipasi seluas mungkin. Ini termasuk, dalam konteks komunikasi, dengan menyediakan juru bahasa isyarat atau alat bantu yang diperlukan.
Pasal 24 Undang-Undang Penyandang Disabilitas juga secara jelas mengatur hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi bagi penyandang disabilitas. Hak itu meliputi hak untuk berkomunikasi melalui bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif.
Maka, memaksa penyandang disabilitas untuk berkomunikasi tanpa alat bantu tak ubahnya melanggar hak mereka dalam undang-undang. Menteri Risma jelas keliru kalau menganggap ketidakmampuan bicara seorang tuli adalah karena kurang dilatih. Dengan logika yang sama, mengapa tidak sang menteri saja yang berlatih berbahasa isyarat agar mampu berkomunikasi dengan mereka?
Boleh jadi Risma terbelenggu dalam paradigma ableisme, yang melihat komunikasi (lisan) sebagai satu-satunya cara berinteraksi. Penyandang disabilitas pendengaran sebenarnya mampu berkomunikasi, tapi sang pejabat enggan melayani kebutuhan khusus mereka dalam berkomunikasi. Perilaku Risma tersebut sama saja dengan memaksakan kehendak agar penyandang disabilitas berkomunikasi layaknya non-difabel dan hal itu merupakan sebuah bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Jika pejabat sekelas Menteri Sosial, yang notabene mengemban tugas untuk mengurusi hak-hak penyandang disabilitas, saja masih berpandangan seburuk itu, wajar apabila diskriminasi terhadap penyandang disabilitas kerap terjadi dalam banyak layanan publik.
Selama ini penyandang disabilitas kerap terlupakan, terutama dalam banyak aspek keadilan, Misalnya, ketika mereka bersaksi di pengadilan, kesaksiannya kerap ditolak karena dianggap tidak bernilai pembuktian. Penolakan itu terjadi karena seorang penyandang disabilitas netra, misalnya, dipandang tidak mampu memenuhi kualifikasi hukum sebagai saksi lantaran hukum acara kita masih menggunakan paradigma yang bias ableisme. Hukum kita masih mensyaratkan bahwa saksi harus dapat melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa. Karena rumusan itulah, banyak penyandang disabilitas yang terasingkan dari keadilan karena kasusnya dianggap tidak bisa dibuktikan.
Belakangan, Risma mengaku telah memaksa penyandang disabilitas itu berbicara dengan alasan bahwa Tuhan telah menganugerahi kita mulut untuk dilatih berbicara. Alasan ini terlampau apologetis. Sebab, bukankah Tuhan juga menganugerahi kita akal dan empati agar lebih peka melihat keragaman kondisi manusia?
Sebagai pejabat publik, Risma tidak hanya melanggar etika publik, tapi juga hak penyandang disabilitas. Atas nama kepastian dan kesetaraan dalam hukum, sang menteri setidaknya harus diberi sanksi atas perilaku memalukannya sebagai pejabat yang tidak peka terhadap kondisi penyandang disabilitas. Hal ini penting sebagai pembelajaran agar kasus serupa tak berulang.
Penulis: Auditya Saputra
