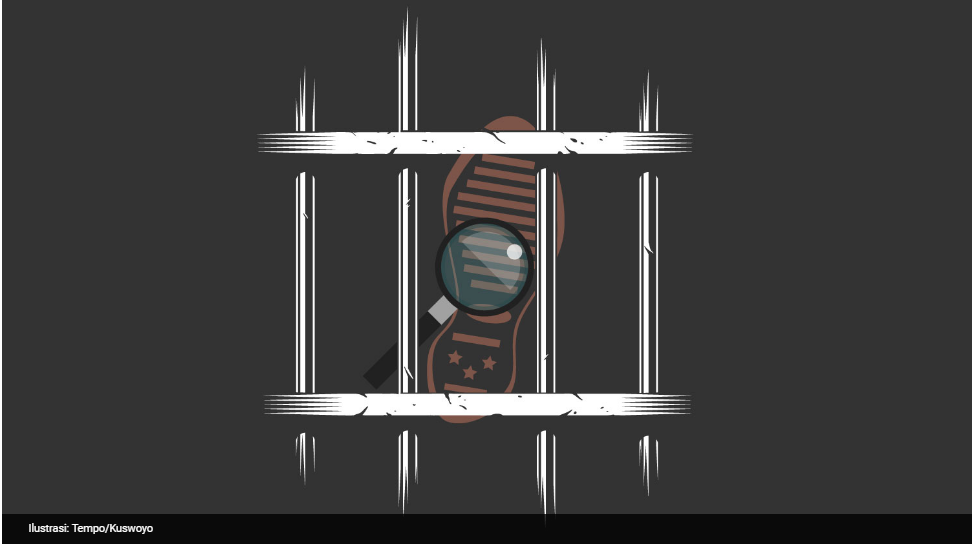 Pemberangusan riset dapat muncul dengan banyak wajah. Penggunaan jalur hukum, alih-alih akademik, untuk merespons temuan penelitian ilmiah merupakan satu dari banyak modus untuk mendiskreditkan ilmu pengetahuan
Pemberangusan riset dapat muncul dengan banyak wajah. Penggunaan jalur hukum, alih-alih akademik, untuk merespons temuan penelitian ilmiah merupakan satu dari banyak modus untuk mendiskreditkan ilmu pengetahuan
Dua pejabat publik belum lama ini melaporkan peneliti dan pembela hak asasi manusia ke polisi dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Fatia Maulida serta menggugat mereka secara perdata sebesar Rp 100 miliar. Adapun Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko melaporkan dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha dan Miftahul Choir. Kedua kasus berawal dari hasil riset yang kemudian dipublikasikan dan didiskusikan secara terbuka.
Tidak hanya menyingkap watak antikritik, gugatan itu juga memperlihatkan gejala antisains di kalangan pejabat publik kita. Antisains merupakan kecenderungan untuk menyangkal dan menolak kaidah-kaidah ilmiah, termasuk hasil penelitian. Masyarakat perlu mewaspadai gelagat ini karena akan berdampak buruk bagi kemajuan ilmu pengetahuan
Hasil riset tidak selayaknya diasosiasikan dengan fitnah atau pencemaran nama. Sebab, dimensi realitas yang diulas oleh riset berbeda. Menyamakan pembuktian riset dengan pembuktian hukum itu seperti merancukan pagar batas antara pengetahuan dan fakta.
Ada alasan mengapa hasil akhir dari suatu penelitian disebut pengetahuan, bukan “fakta”. Pengetahuan merupakan hasil penalaran atau amatan seseorang tentang gejala yang diteliti sesuai dengan kaidah keilmuan tertentu. Ia mendekati kebenaran dalam arti probabilitas sehingga bisa dibantah. Sedangkan fakta dalam hukum dimaknai sebagai peristiwa nyata yang disaksikan, didengar, atau dirasa secara indrawi.
Tidak semua pengetahuan adalah fakta, seperti halnya tidak semua fakta otomatis jadi pengetahuan. Akan menjadi tradisi yang buruk apabila sebuah kebenaran riset justru diuji oleh pengadilan, alih-alih oleh forum akademik yang kompeten.
Berbeda dengan pembuktian hukum, yang digali secara empiris lewat alat bukti, ukuran kebenaran riset tidak terbatas pada aspek empiris. Bayangkan jika ukuran kebenaran riset sebatas ada-tidaknya bukti empiris, maka akan mustahil bagi seorang Georges Lemaitre membuktikan Teori Big Bang yang terjadi miliaran tahun silam. Tentu sang ilmuwan tidak menggunakan mesin waktu untuk menyaksikan sendiri ledakan dahsyat itu agar sampai pada teorinya, melainkan melakukan penalaran atas temuan-temuan yang terpola.
Dengan perangkat penalaran itu pula, penelitian bisa menjangkau gagasan yang melampaui pembuktian empiris. Contohnya dalam Teori Big Bang tadi. Meski belum bisa dipastikan sebagai fakta, teori tersebut nyatanya diterima khalayak sebagai pengetahuan.
Para cendekiawan beraliran rasionalisme, seperti Descartes, Hegel, hingga Chomsky, pun bersepakat bahwa pengetahuan, meskipun belum didukung bukti-bukti empiris, bisa diterima kebenarannya sepanjang bangunan penalarannya membentuk konklusi yang koheren, kohesif, logis, dan memenuhi kaidah keilmuan. Model penalaran jenis ini juga lumrah diterapkan dalam pelbagai penelitian investigatif, termasuk oleh jurnalis, ketika data-data konklusif sulit didapat karena bersifat rahasia. Akibat keterbatasan itu, hasil penyelidikan lazim dipaparkan sebagai dugaan ilmiah (hipotesis) yang dapat dipertanggungjawabkan.
Berbeda dengan fakta, pertanggungjawaban kebenaran riset berada di lapisan metodologis. Kesahihan metodologi diukur dari ketaatan dalam proses pengumpulan data, pengolahan, dan pengambilan kesimpulannya sesuai dengan kaidah sains.
Kebenaran metodologi juga memungkinkan riset dengan tajuk yang sama menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Riset kualitatif menggunakan studi pustaka akan sangat mungkin menghasilkan temuan yang berbeda dengan metode kuantitatif seperti survei. Karena relativitas inilah, tradisi keilmuan selalu memberi ruang untuk saling mengoreksi temuan-temuan riset melalui penelitian tandingan.
Membaca klaim riset juga harus tuntas dan tidak bisa sepotong-sepotong, apalagi sengaja dilepaskan dari konteks untuk sekadar mempermasalahkan diksi penulisnya. Sebab, kesimpulan riset tidak bisa diceraikan dari asumsi-asumsi teoretis yang membentuknya.
Selain itu, ilmiah-tidaknya temuan riset diukur dari perangai penelitinya. Berperangai ilmiah berarti menerima setiap kemungkinan bahwa klaim riset dapat keliru atau terbantahkan. Maka, perangai itu tecermin dari pilihan kata seperti “potensi” atau “dugaan” dalam teks wacana riset, yang mengisyaratkan sang peneliti mengakui adanya kondisi atau faktor lain di luar medan telaah sebagai keniscayaan.
Pemberangusan riset dengan cara-cara hukum menjadi hambatan bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Di satu sisi, melapor ke polisi memang merupakan hak setiap orang. Namun pilihan itu sama sekali bukan cara yang bijak dalam menyikapi temuan penelitian. Apalagi pelapornya adalah pejabat publik, yang hampir pasti diuntungkan oleh relasi kuasanya.
Pendekatan punitif akan semakin mengekang kebebasan akademik yang belakangan kian sempit. Cukuplah Saiful Mahdi menjadi nama terakhir yang dibui lantaran sikap kritisnya.
Jejak pemidanaan terhadap peneliti pada gilirannya juga akan menyurutkan minat masyarakat untuk membuat riset-riset kritis demi kepentingan publik. Kemunduran seperti itu perlu dicegah karena kualitas riset di Indonesia masih sangat rendah ketimbang di negara lain.
Pukulan balik terhadap masyarakat sipil dalam bentuk pelaporan ke polisi dan gugatan, bagaimanapun, akan semakin memperkuat kesan antikritik otoritas. Karena dimandatkan untuk mengurus hajat hidup orang banyak, pejabat publik tak boleh alergi apabila kinerjanya dikritik, apalagi lewat riset.
Semestinya penelitian ilmiah disadari sebagai wujud partisipasi paling total dan bermartabat dari rakyat kepada pejabat. Bukankah pemerintah sendiri yang sering mengatakan bahwa sebaik-baiknya kritik adalah yang berbasiskan data? Dengan kata lain, riset seharusnya diapresiasi, bukan malah diberangus.
Asumsi bahwa pemidanaan dengan sendirinya menggugurkan kebenaran riset juga keliru. Ilmu pengetahuan mengenal tradisi dialektika yang memperlakukan sebuah tesis sebagai valid sepanjang belum datang antitesis yang membatalkannya. Artinya, penjatuhan vonis pidana sekalipun tidak otomatis menggugurkan validitas penelitian yang diperkarakan. Maka, jika pelapor sungguh-sungguh ingin menyelesaikan polemik ini, cara yang paling tepat bukanlah pemidanaan melainkan menggunakan koridor ilmiah yang tersedia.
Penulis : Auditya Saputra
